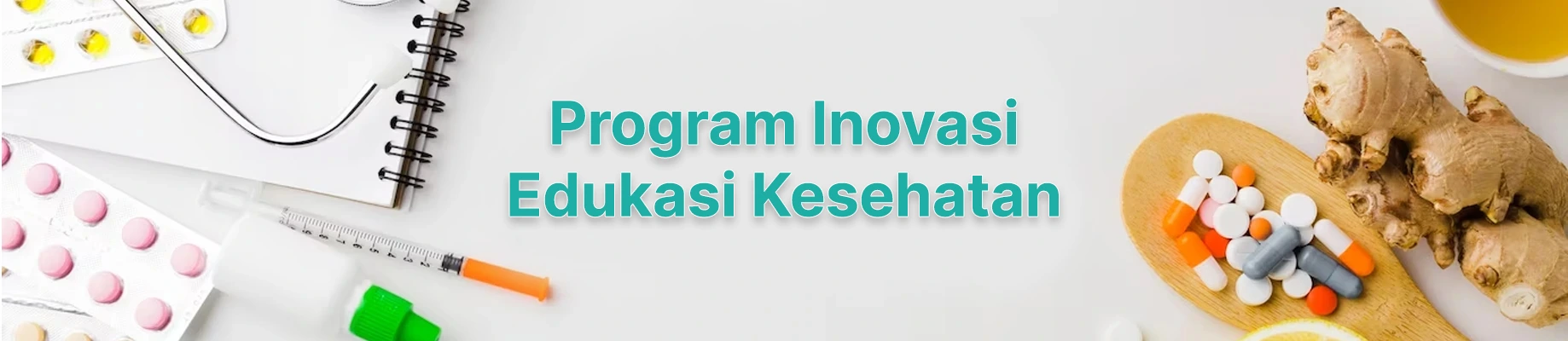
Contoh Aplikasi TPB untuk Diagnosis Perilaku

Sampai awal 2000an, TPB atau Theory of Planned Behaviour adalah teori yang paling sering dipakai riset perilaku (Armitage & Conner, 2001). Dalam meta-analysis 185 studi tahun 1997, dikatakan TPB mampu menjelaskan 27% varians perilaku. Lumayan banget. Karena itu, walau tidak lagi digunakan sebagai teori utama, praktisi komunikasi sebaiknya menguasai TPB. Kalau bukan untuk menambah wawasan, paling tidak untuk diagnosis masalah komunikasi.
TPB, yang dikembangkan dari TRA (Theory of Reasoned Action) menempatkan intention atau keinginan kuat atau kesiapan berperilaku sebagai faktor penentu perilaku. Tiga faktor yang mempengaruhi intention, yang kemudian jadi fokus TPB, adalah 1) Sikap (attitude), 2) norma subjektif (subjective norms), dan 3) persepsi tentang kemudahan melakukan perilaku (perceived behaviour control).
Yang pertama atau sikap terdiri dari 2 dimensi, yaitu 1) kepercayaan terhadap outcome (manfaat/ risiko) dari perilaku, 2) penilaian terhadap manfaat/ risiko perilaku itu sendiri (positif/ negatif atau penting/ tidak penting).
Yang kedua, norma subjektif terdiri dari 1) pandangan seseorang tentang bagaimana orang-orang bermakna di sekelilingnya bersikap terhadap perilaku (mendukung atau tidak) dan 2) bagaimana sikap seseorang itu terhadap anjuran orang-orang di sekelilingnya itu (mau mengikuti atau tidak).
Yang terakhir adalah menyangkut seberapa mudah seseorang melakukan perilaku itu. 1) Apakah seseorang memiliki sumber daya atau sebaliknya, hambatan-hambatan untuk melakukan perilaku itu? Lalu, 2) sebesar besar menurutnya sumber daya yang dimiliki atau hambatan-hambatannya?
Agar perilaku terjadi, orang mesti bersikap positif, ber-norma subjektif positif, dan mempersepsikan perilaku mudah dilakukan.
Berikut contoh aplikasi pada olah raga. Bila seseorang percaya jalan kaki di atas 45 menit dapat memangkas lemak di tubuh dan baginya, memangkas lemak tidak penting (negatif) karena tubuhnya terbilang kurus, maka sikapnya tidak positif. Dia tak akan memilih olahraga jalan kaki > 45 menit.
Agar bersikap positif, kita mesti mencari manfaat atau risiko yang dipercaya dan sekaligus dipandang positif. Bukan hanya menurut data ilmiah tapi juga menurut warga. Di sini, lensa ilmiah dan warga mesti beririsan. Riset perlu dilakukan untuk menemukan pesan yang klop.
Kalau pun bersikap positif tapi bila orang-orang di sekitarnya, yang dia hargai, tidak mendukung, misalnya mereka mengatakan udara Jakarta buruk dan jalan kaki justru berbahaya dan di sisi lain, dia ingin mengikuti nasihat-nasihat di sekelilingnya, maka perilaku juga sulit terjadi.
Pemahaman tentang norma subjektif menentukan siapa yang perlu disasar. Kalau para ibu memiliki sikap positif terhadap jalan kaki tapi para suami, yang mereka ikuti, tidak mendukung, maka intervensi komunikasi tentu utamanya bukan ditujukan bagi para ibu. Salah alamat namanya.
Yang terakhir, kita perlu mempelajari hal-hal yang dimiliki orang untuk berperilaku? Sendal, sepatu, pakaian olah raga, jalanan yang aman (dari polusi atau tindak kriminal) atau entah apa, yang lainnya? Lalu, seberapa memadai yang mereka miliki? Seandainya, mereka punya sepatu, pakaian olah raga dan jalanan di sekitar dipandang aman, maka dengan sikap positif dan norma subjektif positif, akan terbangun intensi kuat dan perilaku pun akan terjadi. Tapi kalau ada yang negatif, perilaku sulit terjadi
WTC, 19 September 2023 - RR



