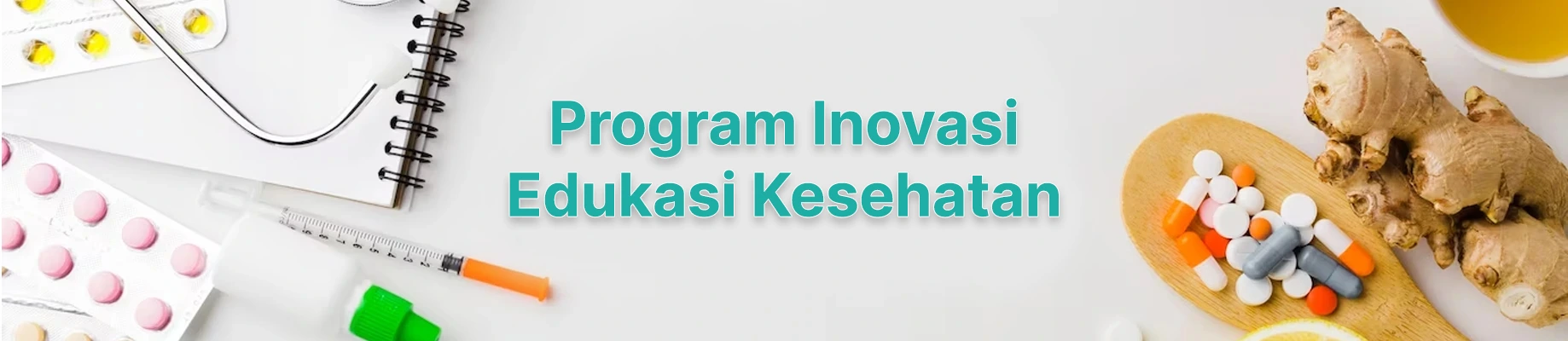
Jangan Sendirian Menangani Rabies

Seorang kawan mengabarkan rabies mewabah di daerahnya. Per 25 April, 6 orang meninggal.
Virusnya ditularkan melalui gigitan hewan terinfeksi yang kemudian menyerang sistem saraf pusat. Penanganan terlambat berakibat fatal, kematian, dengan cara tragis. Sebelumnya, orang akan mengalami kejang, takut air (hidrofobia), takut cahaya (fotofobia).
Dalam perspektif KAP, wabah rabies merupakan contoh masalah yang kental dimensi sosial ketimbang hanya individual atau privat. Yang digigit memang orang per orang tapi hewan yang menggigit belum tentu milik orang yang digigit. Kebanyakan malah bukan.
Sebelumnya, di daerah lain, dikabarkan seorang anak meninggal setelah sebelumnya digigit anjing. Penanganannya terlambat gara-gara pemilik anjing tidak segera mengabarkan kematian anjing beberapa waktu kemudian (tanda anjing terinfeksi).
Maka dari itu, intervensi perilaku dalam wabah rabies mesti menyasar dimensi sosial. Setidaknya untuk sejumlah tujuan berikut.
Pertama, membangun kesepakatan komunitas di masa wabah, termasuk cara memelihara hewan (tidak membiarkan berkeliaran), mengabarkan bila ada kematian, mewaspadai hewan luar yang masuk, dan lain-lain.
Kesepakatan komunitas perlu dibentuk untuk menghindari konflik sesama warga. Juga, mengesahkan tekanan pada individu-individu yang “bandel”.
Kesepakatan komunitas hanya bisa terbangun bila warga atau wakil warga aktif berpartisipasi. Bukan menjadi penonton tapi narasumber. Di sini, edukator menggunakan topi fasilitator. Dia tidak mengajari namun mengembangkan ruang nyaman agar semua berbicara, berpendapat, saling mendengarkan untuk saling memahami, memilih opsi, dan mengikat diri dalam kesepakatan.
Kalau pun menyampaikan informasi, edukator hanya melakukannya dalam rangka memicu atau memancing warga berbicara.
Kedua, membuat dan menghidupkan artefak budaya oral, yang menuntun perilaku warga dan juga bisa turun dari generasi ke generasi. Yang dimaksud disini adalah lagu, cerita, permainan, atau bentuk lainnya yang langgeng. Seperti Smong di Pulau Simeulue yang dibuat 1900an, untuk mengingatkan warga akan Tsunami, di tahun 2004, saat gempa besar memicu Tsunami besar di NAD, Smong banyak berperan mengarahkan perilaku warga mencari perlindungan (ke tempat tinggi).
Artefak budaya moral ini bisa disusun oleh budayawan dan tokoh-tokoh setempat, termasuk tokoh agama. Atau, dalam jangka pendek, pinjam saja dari produk budaya oral yang ada, seperti lagu, salawatan, cerita, dll.
Singkatnya, masalah rabies tak bisa dituntaskan dengan pendekatan individualistik, seperti memberi himbauan atau sosialisasi semata. Kasihan nanti yang mau menasehati tetangganya, bisa berantem.
Pasar Minggu, 29 April 2025 – RR/ Forum KAP



