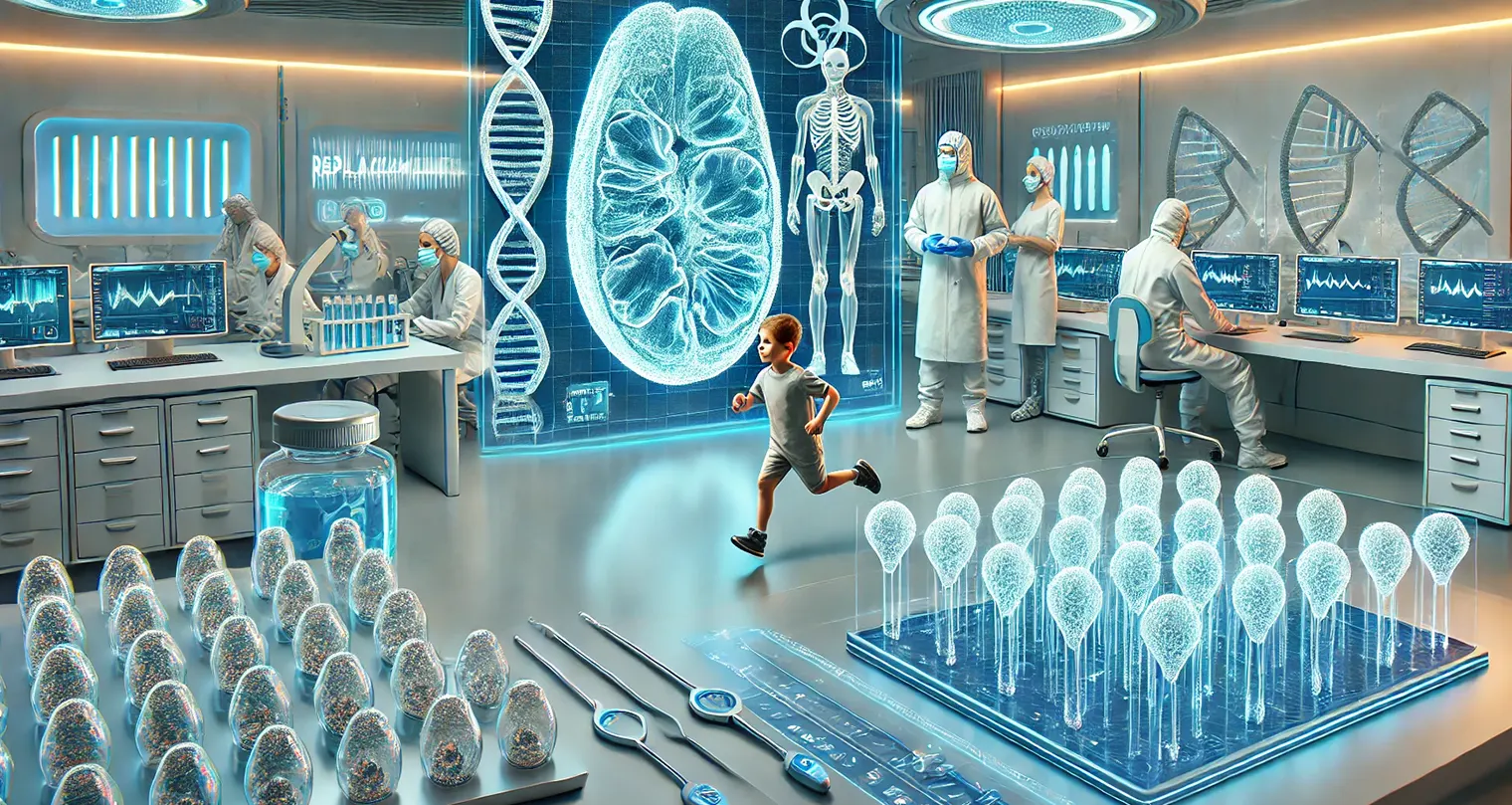Ada rumah yang pintunya masih bisa dibuka, tetapi ruang tamunya tak lagi benar-benar “hidup”. Kursi tertutup kardus, meja makan berubah menjadi pulau-pulau barang, dapur tinggal lorong selebar badan. Di beberapa rumah, tempat tidur pun menyisakan satu jalur sempit—seperti garis batas antara tubuh yang ingin istirahat dan tumpukan yang tak mau bergeser.
Dari luar, orang mudah menebak. Label jatuh cepat: pemalas, jorok, tidak disiplin. Kalimatnya pendek, nadanya menghakimi. Padahal pada banyak kasus, yang sedang terjadi bukan sekadar berantakan. Ini bisa merupakan Hoarding Disorder—gangguan kesehatan jiwa yang membuat seseorang sangat sulit berpisah dengan barang, merasa “harus menyimpan”, dan mengalami distres yang nyata saat membuang, hingga ruang hidup tersumbat dan fungsi rumah runtuh pelan-pelan.
Di titik ini, hoarding bukan masalah estetika. Ia berubah menjadi masalah keselamatan, kesehatan, relasi, bahkan martabat.
Dari kebiasaan menjadi diagnosis
Untuk waktu yang lama, perilaku menimbun kerap ditafsirkan sebagai bagian dari OCD atau sekadar kebiasaan yang “keterlaluan”. Riset kemudian menunjukkan sesuatu yang lebih spesifik: motivasi menimbun tidak selalu sama dengan OCD; pola komorbiditasnya khas; dampaknya meluas; respons terhadap intervensi tertentu pun berbeda. Karena itulah sejak DSM-5 (2013), Hoarding Disorder diakui sebagai diagnosis tersendiri dalam kelompok Obsessive-Compulsive and Related Disorders.
Perubahan ini penting bukan hanya untuk dunia psikiatri. Ia menggeser cara publik memandang: dari “kurang niat” menjadi “ada mekanisme gangguan”, dari “tinggal dibuang” menjadi “ada luka, ada ketakutan, ada sirkuit otak yang bekerja berbeda”.
Kapan “menyimpan” menjadi gangguan?
Menyimpan barang adalah hal manusiawi. Kolektor merawat koleksinya dengan rapi; seseorang menyimpan surat lama karena sentimental; keluarga menyimpan buku karena nilai edukasi. Dalam batas tertentu, menyimpan adalah cara merawat memori, pengetahuan, dan identitas. Hoarding berbeda bukan karena jumlah semata, melainkan karena dua hal yang lebih menentukan: fungsi ruang dan distres. Ketika rumah tidak lagi bisa dipakai sebagai rumah, dan ketika upaya melepas barang memicu penderitaan emosional yang nyata, di situlah “menyimpan” mulai bergeser menjadi gangguan.
Secara sederhana, kriteria inti menekankan adanya kesulitan menetap untuk membuang atau berpisah dengan barang—apa pun nilai barang itu di mata orang lain. Kesulitan ini bukan karena lupa atau semata malas, melainkan karena dorongan kuat untuk menyimpan disertai tekanan emosional saat harus membuang. Akibatnya, barang menumpuk hingga area rumah tersumbat dan tidak bisa dipakai sesuai fungsinya—ruang tamu tak lagi menerima tamu, meja makan tak lagi menjadi tempat makan, dapur tak lagi aman untuk memasak, kamar tidur tak lagi memberi istirahat yang layak. Lebih jauh, penumpukan ini menimbulkan gangguan bermakna: mengganggu kerja, relasi, kesehatan, atau keamanan hunian. Dan, yang penting, pola ini tidak lebih baik dijelaskan oleh kondisi medis tertentu atau gangguan mental lain.
Ada dua penanda yang sering luput karena orang hanya melihat “barang di rumah”, bukan “cara hidup” yang terbentuk. Pertama, excessive acquisition—kebiasaan membeli, mengambil gratis, atau “mengadopsi” barang terus-menerus, seolah rumah menjadi magnet yang tak pernah kenyang. Yang kedua adalah insight—tingkat kesadaran terhadap masalah. Ada yang sadar perilakunya merusak hidupnya, tetapi merasa tak sanggup mengubah. Ada yang setengah sadar: tahu ada masalah, namun selalu menemukan pembenaran. Ada pula yang hampir sepenuhnya yakin semuanya baik-baik saja, sehingga setiap ajakan mencari bantuan terasa bukan sebagai pertolongan, melainkan ancaman.
Di titik itu, hoarding bukan lagi soal “punya barang banyak”. Ia menjadi soal kemampuan untuk melepaskan, menata, dan hidup aman—tanpa terus-menerus ditarik oleh ketakutan, penyesalan, dan dorongan menyimpan yang terasa lebih kuat daripada logika.
Barang sebagai jangkar emosi
Bagi banyak orang dengan hoarding, benda bukan benda. Ia menjadi arsip identitas: “ini aku dulu”, “ini mimpiku”, “ini bukti bahwa aku pernah bertahan”. Ada yang melekat pada barang karena sentimentalitas; ada yang karena rasa takut “nanti dibutuhkan”; ada yang karena keyakinan moral “tidak boleh menyia-nyiakan”. Pada sebagian orang, benda bahkan diperlakukan seolah punya perasaan—dibayangkan “tersakiti” jika dibuang.
Di balik semua itu, ada tema yang berulang: kehilangan kendali. Barang memberi ilusi kontrol yang mudah: disusun (atau ditumpuk) sesuai cara sendiri, aman dari penilaian orang, tidak menuntut timbal balik seperti relasi manusia. Ketika hidup pernah memberi luka—duka, perceraian, kemiskinan, trauma, kesepian panjang—barang bisa menjadi selimut psikologis. Hangatnya semu, tetapi menenangkan sesaat. Masalahnya, selimut itu lama-lama menutup napas.
Otak yang kewalahan oleh keputusan kecil
Banyak orang mengira membuang adalah tindakan sederhana. Pada hoarding, membuang bisa terasa seperti ujian besar. Kertas bon, kaus usang, kabel tak terpakai—bagi orang lain remeh, bagi penderita hoarding bisa memantik debat batin yang melelahkan: “kalau ini dibuang, aku menyesal”, “kalau ini dibutuhkan, aku gagal”, “kalau aku salah memilih, ada konsekuensi besar”.
Riset neuroimaging dan kajian neuropsikologi mengarah pada masalah di ranah fungsi eksekutif: merencanakan, mengorganisasi, mengelompokkan, memprioritaskan, mengambil keputusan. Ada sinyal bahwa sirkuit otak yang mengatur penilaian nilai, salience (“ini penting!”), emosi saat mengambil keputusan, dan kontrol diri dapat bekerja secara berbeda. Akibatnya, proses memilah yang bagi orang lain cepat, bagi penderita hoarding menjadi medan perang: terlalu banyak pilihan, terlalu banyak makna, terlalu banyak rasa takut.
Perfeksionisme sering ikut menambah beban. “Kalau memilah, harus sempurna.” Dan ketika standar sempurna itu mustahil, pilihan yang tersisa adalah menunda. Menunda memberi lega sesaat; otak belajar bahwa menghindar adalah cara cepat menurunkan cemas. Di sinilah penguatan negatif bekerja seperti mesin: makin menunda, makin terasa “selamat”—dan makin susah memulai.
Genetik: kerentanan, bukan vonis
Hoarding juga punya sisi biologis. Studi pada kembar mengindikasikan kontribusi genetik pada variasi gejala hoarding berada pada kisaran sedang. Namun ini bukan cerita satu gen tunggal. Arah besarnya cenderung ke poligenik: banyak variasi gen kecil yang, bersama pengalaman hidup dan perkembangan otak, membentuk kerentanan. Beberapa temuan populasi juga memberi petunjuk adanya keterkaitan risiko genetik lintas-trait (misalnya dengan spektrum tertentu seperti skizofrenia atau autisme pada level gejala), walau hubungan ini tidak berarti “hoarding sama dengan” gangguan-gangguan tersebut.
Kalimat yang paling adil adalah: biologi menyiapkan panggung, hidup menulis naskah, kebiasaan menguatkan adegan.
Mekanisme pertahanan jiwa yang tampak sehari-hari
Istilah mekanisme pertahanan jiwa bukan ditujukan untuk menyalahkan, apalagi memberi cap “sengaja begitu”. Ia adalah cara psikologi membaca strategi bertahan yang bekerja diam-diam ketika seseorang merasa terancam—oleh kehilangan, rasa malu, cemas, atau ketidakpastian. Pada hoarding, pertahanan ini sering tampil bukan sebagai kata-kata besar, melainkan sebagai kebiasaan kecil yang terus berulang, sampai akhirnya menjadi pola hidup.
Salah satu yang paling sering terlihat adalah denial—penyangkalan halus yang mengecilkan dampak. “Ini cuma agak berantakan,” katanya, sambil melangkahi tumpukan di lorong. Bukan karena ia tidak bisa melihat, melainkan karena mengakui kenyataan terasa terlalu menyakitkan. Mengakui berarti membuka pintu pada rasa bersalah, pada ketakutan kehilangan, pada kemungkinan bahwa rumah—dan hidup—sudah bergeser jauh dari yang ia bayangkan.
Ada pula rasionalisasi: alasan yang terdengar sangat masuk akal di permukaan. Barang-barang disimpan atas nama “investasi”, “nanti buat amal”, “bahan penelitian”, “sayang kalau dibuang”. Kalimatnya rapi, argumennya meyakinkan. Namun di balik itu, sering ada sesuatu yang lebih dalam: kebutuhan untuk membenarkan rasa “harus menyimpan”, agar dorongan yang emosional terasa logis dan bermartabat. Rasionalisasi memberi pelindung: kalau alasan terdengar benar, maka kecemasan dan rasa malu bisa ditekan.
Pertahanan berikutnya adalah avoidance—menghindar. Menghindar di sini bukan sekadar menunda pekerjaan rumah, melainkan menghindar dari keputusan yang memicu nyeri batin. Memilah berarti memilih; memilih berarti berpisah; berpisah berarti menghadapi kecemasan dan duka kecil yang mungkin terasa tak tertahankan. Karena itu, proses memilah sering ditinggalkan di tengah, atau tidak dimulai sama sekali. Menghindar memberi lega sesaat, dan justru karena “lega” itulah perilaku ini semakin mengakar.
Dalam beberapa kasus, emosi dari sumber lain bisa bergeser menjadi kontrol atas benda—ini yang dalam psikologi disebut displacement. Konflik keluarga, perasaan ditinggalkan, pengalaman kehilangan, atau luka yang tidak pernah selesai, seolah dipindahkan ke arena yang lebih “aman”: barang. Mengatur barang terasa lebih mungkin daripada mengatur hidup. Menentukan nasib sebuah benda terasa lebih mudah daripada menata ulang relasi, menghadapi kesepian, atau menelan kenyataan yang pahit.
Ada juga isolation of affect: seseorang bisa berbicara datar, bahkan tenang, saat menjelaskan tumpukan barangnya. Ia tampak “baik-baik saja”. Tetapi ketika satu kantong barang diminta untuk dibuang, reaksi emosinya bisa meledak—marah, panik, menangis, atau seperti kehilangan kendali. Seakan-akan emosi lama yang selama ini dikunci rapat, tiba-tiba menemukan pemicu yang tepat. Di sinilah keluarga sering kaget: “Kenapa reaksinya berlebihan?” Padahal, yang “berlebihan” itu sering bukan tentang kantong tersebut, melainkan tentang sejarah emosi yang menumpuk di belakangnya.
Orang luar sering hanya melihat “keras kepala”. Yang jarang terlihat adalah sistem pertahanan yang sudah lama bekerja—kadang sejak kecil—dan pernah menjadi cara paling masuk akal untuk bertahan. Pada hoarding, pertahanan itu tidak hilang; ia hanya berubah bentuk menjadi tumpukan yang perlahan mengambil alih ruang, sampai akhirnya seseorang tidak sekadar menyimpan barang, tetapi ikut tersimpan di dalamnya.
Imunologi: menarik, tetapi harus jujur
Di era psikoneuroimunologi, publik sering mendengar “peradangan otak” dan berharap ada tes darah yang bisa menjelaskan segalanya. Untuk hoarding, kita perlu jujur: belum ada biomarker imunologi yang tervalidasi khusus untuk dipakai mendiagnosis atau memandu terapi hoarding di klinik.
Yang lebih masuk akal saat ini adalah pemahaman umum: stres kronik, kurang tidur, isolasi sosial, depresi atau kecemasan (yang sering komorbid) dapat berkaitan dengan inflamasi derajat rendah; dan inflamasi sistemik dapat memengaruhi mood serta fungsi kognitif. Di sisi riset psikiatri yang lebih luas, muncul temuan tentang subkelompok gangguan mental yang menunjukkan “signature” inflamasi tertentu dan cenderung merespons terapi standar lebih buruk. Ini membuka pintu imajinasi ilmiah: mungkin saja suatu hari ada subtipe hoarding yang lebih terkait proses inflamasi—tetapi itu masih wilayah yang membutuhkan bukti spesifik, bukan klaim klinis hari ini.
Di antara hype dan harapan, posisi paling sehat adalah: penasaran, tetapi tidak tergesa.
Seberapa sering terjadi, dan kapan mulai?
Perkiraan prevalensi hoarding klinis bervariasi antarstudi, sering berada di kisaran beberapa persen populasi. Yang relatif konsisten: gejala kerap mulai muncul sejak remaja atau dewasa muda, lalu meningkat perlahan dari dekade ke dekade bila tidak ditangani. Pada usia lebih tua, masalahnya tampak lebih nyata—sebagian karena progresif, sebagian karena “penyangga sosial” berkurang: pasangan meninggal, anak pindah, tenaga dan fokus menurun.
Hoarding jarang datang sendirian. Depresi, gangguan cemas, fobia sosial, hingga ADHD (terutama inatensi) sering menjadi teman seperjalanan. Komorbiditas ini bukan sekadar “tambahan label”; ia bisa memperparah energi, fokus, dan kemampuan organisasi sehingga tumpukan makin sulit dikendalikan.
Dari barang ke risiko kesehatan publik
Tumpukan barang mengubah rumah menjadi medan risiko.
Jalur sempit meningkatkan risiko jatuh—terutama pada lansia. Barang mudah terbakar, akses keluar yang tertutup, dan kabel yang semrawut meningkatkan risiko kebakaran. Debu, jamur, hama, sanitasi buruk, luka yang sulit dirawat—semuanya dapat muncul sebagai masalah kesehatan fisik. Ditambah rasa malu yang membuat orang menutup pintu bagi tamu, tetangga, bahkan keluarga. Isolasi sosial tumbuh subur di ruang yang sesak.
Pada titik tertentu, hoarding menjadi isu kesehatan publik: keselamatan hunian, kesehatan lansia, beban caregiver, dan potensi konflik sosial.
Diagnosis: lebih dari sekadar melihat rumah
Diagnosis hoarding disorder bukan urusan “sekilas pandang”. Ia tetap menjadi ranah profesional kesehatan mental—psikiater atau psikolog klinis—karena yang dinilai bukan cuma tumpukan barang, melainkan keseluruhan ekosistem psikologis di belakangnya: cara seseorang memaknai benda, pola pengambilan keputusan, mekanisme menghindar, komorbiditas (depresi, cemas, OCD, ADHD, trauma), tingkat insight (seberapa sadar ia bahwa ini masalah), serta risiko keselamatan dan dampaknya pada fungsi hidup sehari-hari.
Wawancara klinis menjadi fondasi, tetapi klinisi tidak bekerja hanya dengan intuisi. Ada alat bantu yang membuat penilaian lebih objektif dan terukur. Saving Inventory–Revised (SI-R) membantu memetakan dimensi inti—kesulitan membuang, tingkat kekacauan (clutter), dan kecenderungan akuisisi. Hoarding Rating Scale–Interview (HRS-I) memberikan format wawancara singkat untuk menilai intensitas gejala dan gangguan fungsi. Sementara Clutter Image Rating (CIR)—serangkaian gambar tingkat kekacauan—sering menjadi “bahasa bersama” agar persepsi pasien, keluarga, dan tenaga kesehatan bisa bertemu; apa yang dianggap “masih wajar” oleh seseorang bisa ternyata sudah masuk zona berbahaya menurut orang lain.
Bagian yang tidak kalah penting adalah diagnosis banding. Banyak kondisi tampak mirip di permukaan, tetapi mesin dalamnya berbeda. Koleksi hobi yang tertata, kuratorial, dan tidak mengganggu fungsi ruang bukanlah hoarding. Depresi berat dapat membuat rumah kacau karena energi dan motivasi merosot, bukan karena keterikatan emosional pada barang. Pada OCD, perilaku menyimpan biasanya didorong obsesi spesifik dan ritual untuk meredakan kecemasan. Psikosis dapat melibatkan delusi tentang “makna khusus” atau fungsi “istimewa” sebuah barang. Demensia dan gangguan neurokognitif dapat mengubah penilaian serta kemampuan organisasi. Pada spektrum autisme, minat sempit dan pola ritualistik kadang tampak seperti menimbun, tetapi motif dan pola kognitifnya bisa berbeda.
Kata kuncinya: mirip di permukaan, berbeda di mesin dalam. Dan di situlah diagnosis yang teliti menjadi pintu pertama—bukan untuk memberi cap, melainkan untuk menentukan bantuan yang paling tepat.
Jalan keluar yang sering gagal: bersih-bersih paksa
Ada satu “solusi instan” yang hampir selalu menggoda keluarga: membersihkan diam-diam, membuang cepat, menyewa truk, menyelesaikan dalam sehari.
Pada hoarding, ini sering menjadi bumerang. Bukan karena penderita “tidak tahu berterima kasih”, melainkan karena pembersihan paksa bisa traumatik, memutus kepercayaan, dan memicu akuisisi ulang. Tumpukan kembali—kadang lebih cepat, kadang lebih rapat—seperti tubuh yang bereaksi setelah ancaman.
Pendekatan modern menekankan kolaborasi: aman dulu, fungsional dulu, baru rapi kalau memungkinkan.
Terapi: membangun keterampilan, bukan sekadar membuang
Terapi hoarding yang efektif berangkat dari satu pengakuan sederhana: masalahnya bukan semata “barang terlalu banyak”, melainkan keterampilan mental dan emosional yang macet ketika seseorang harus memilih—simpan atau buang. Karena itu, standar emas psikoterapi adalah Cognitive Behavioral Therapy (CBT) yang dimodifikasi khusus untuk hoarding. Pendekatan ini tidak berdiri di atas ceramah dan nasihat, tetapi latihan berulang dalam situasi nyata—melatih otak untuk menilai, memilah, dan menoleransi rasa tidak nyaman tanpa lari ke tumpukan.
Di dalam CBT, langkah pertama sering kali adalah menguji keyakinan yang tampak sepele, tetapi menguasai perilaku: “kalau ini dibuang, aku hancur,” atau “kalau tidak disimpan, aku pasti menyesal.” Terapis membantu pasien membedah keyakinan itu menjadi hipotesis, lalu mengujinya lewat pengalaman konkret. Bersamaan dengan itu, pasien dilatih keterampilan yang bagi banyak orang terasa “alami”, tetapi pada hoarding menjadi medan sulit: mengorganisasi, mengkategorikan, memprioritaskan, serta mengambil keputusan yang cukup baik—bukan sempurna. Di titik ini, terapi menggeser target: bukan rapi ideal, melainkan keputusan yang konsisten dan realistis.
Komponen yang paling menantang adalah latihan paparan: membuang secara bertahap dan menahan dorongan untuk mengambil barang baru. Paparan ini bukan kekerasan, melainkan latihan toleransi. Kecemasan yang awalnya terasa seperti gelombang besar, perlahan “belajar turun” ketika seseorang tetap bertahan di situasi membuang tanpa melakukan penghindaran. Karena panggung utama hoarding adalah rumah, terapi sering kali dilakukan in-home—bukan karena ingin menghakimi, tetapi karena perubahan yang nyata harus terjadi di tempat kebiasaan itu hidup.
Banyak pasien datang dengan ambivalensi tinggi: sebagian diri ingin lega, sebagian diri takut kehilangan. Di sinilah motivational interviewing menjadi penopang penting. Tujuannya bukan memaksa, melainkan membantu pasien menemukan alasan internal untuk berubah—alasan yang lebih kuat daripada rasa takut, dan lebih tahan lama daripada sekadar tekanan keluarga.
Farmakoterapi, bila dipakai, bukan “pil hoarding”. Bukti obat masih terbatas dan belum ada obat yang benar-benar spesifik untuk hoarding disorder. Namun obat bisa dipertimbangkan ketika komorbiditas kuat ikut “mengunci” proses terapi—misalnya depresi yang membuat energi nol, kecemasan yang membuat paparan mustahil, atau gejala OCD yang dominan. Pada profil tertentu, klinisi dapat mencoba SSRI atau opsi lain sesuai penilaian klinis, dengan tujuan pragmatis: memperbaiki fungsi harian agar terapi perilaku lebih mungkin dijalankan.
Pada kasus berat—ketika ada risiko kebakaran, infestasi, jalur evakuasi tertutup, atau ancaman kehilangan rumah—pendekatan yang lebih realistis sering berupa harm reduction. Target awal bukan rumah rapi, melainkan rumah yang aman: membuka jalur keluar, membuat dapur dapat dipakai tanpa bahaya, memastikan akses obat dan alat kesehatan, serta menurunkan risiko jatuh. Di tahap ini, kerja tim lintas sektor (kesehatan, layanan sosial, perumahan, hingga pemadam kebakaran) sering lebih efektif daripada satu pihak bergerak sendiri, karena masalahnya sudah melibatkan keselamatan, lingkungan, dan sistem dukungan.
Di luar terapi formal, teknologi bisa menjadi alat bantu praktis yang manusiawi. Dokumen fisik dapat diganti arsip digital; kenangan bisa disimpan lewat foto; bukti transaksi dapat disimpan elektronik. Bukan untuk “memaksa modern”, melainkan untuk mengurangi beban ruang tanpa mencabut rasa aman—sebab pada hoarding, rasa aman sering melekat pada benda, dan terapi yang baik tidak merampas rasa aman itu, melainkan mengajarkan cara baru untuk memilikinya.
Follow-up: mencegah “kambuh diam-diam”
Hoarding cenderung kronis. Karena itu, follow-up bukan formalitas setelah terapi “selesai”, melainkan bagian dari perawatan itu sendiri. Banyak perubahan pada hoarding terjadi pelan—setapak demi setapak—dan kekambuhan pun sering datang dengan cara yang sama: tidak meledak, tidak dramatis, tetapi merayap. Tiba-tiba satu sudut kembali penuh, lalu dua sudut, lalu jalur menyempit lagi. Pada titik tertentu, orang baru sadar ketika rumah sudah kembali “menutup”.
Yang membantu justru hal-hal yang tampak sederhana, tetapi konsisten. Pemantauan berkala—di awal bisa tiap 2–4 minggu, lalu menjadi bulanan—menjaga akuntabilitas tanpa menambah tekanan. Foto ruang sebelum dan sesudah menjadi cermin yang jujur, karena ingatan sering menipu: apa yang terasa “sudah jauh membaik” kadang masih belum aman, atau sebaliknya, kemajuan kecil yang tak terasa ternyata nyata. Clutter Image Rating (CIR) dapat dipakai sebagai patokan bersama agar pasien, keluarga, dan tenaga kesehatan berbicara dalam skala yang sama, bukan sekadar pendapat.
Dalam fase pemeliharaan, aturan “barang masuk” sering lebih menentukan daripada semangat bersih-bersih sesekali. Aturan tidak harus rumit: satu barang masuk, satu barang keluar; atau menetapkan zona rumah yang wajib tetap kosong. Declutter kecil tetapi rutin—10 sampai 20 menit per hari, atau 30 menit beberapa kali seminggu—lebih efektif daripada maraton yang melelahkan lalu berhenti total. Rutinitas kecil membangun kebiasaan baru, dan kebiasaan baru adalah benteng paling kuat untuk mencegah tumpukan kembali.
Daftar tanda bahaya juga penting, karena kambuh sering diawali sinyal-sinyal yang sama: jalur mulai menyempit, barang mulai naik ke tempat tidur, dapur kembali tak bisa dipakai, kantong belanja menumpuk tanpa dibuka, muncul belanja impulsif “sekadar karena diskon”, atau mulai ada rasa ingin menyembunyikan kondisi rumah dari orang terdekat. Ketika tanda-tanda ini muncul, respons yang tepat bukan rasa malu, melainkan kembali ke rencana: memperketat aturan masuk barang, menambah sesi declutter kecil, atau menjadwalkan konsultasi ulang sebelum keadaan membesar.
Follow-up yang baik membuat perubahan tetap hidup—bukan dengan tekanan, tetapi dengan sistem yang menjaga rumah tetap aman, dan menjaga seseorang tetap punya ruang untuk bernapas.
Kalimat yang menolong, bukan melukai
Dalam hoarding, kata-kata bukan sekadar bunyi. Ia bisa menjadi jembatan—atau palu. Satu kalimat yang merendahkan dapat menutup pintu kerja sama berbulan-bulan; satu kalimat yang tepat dapat membuka ruang aman untuk berubah. Karena itu, cara kita berbicara sering sama pentingnya dengan rencana terapi itu sendiri.
Untuk pasien, kalimat yang menolong biasanya tidak dimulai dari tuntutan, melainkan dari tujuan yang manusiawi. “Tujuan kita bukan membuang semua. Tujuan kita mengembalikan rumah yang aman dan hidup yang lebih lega.” Ini menurunkan rasa terancam—karena yang dikejar bukan kehilangan, melainkan keselamatan dan kelapangan. “Kecemasan saat membuang itu nyata—dan bisa dilatih turun.” Kalimat ini mengakui bahwa rasa panik bukan drama; ia respons yang benar-benar terasa di tubuh. Dan yang paling penting, perubahan dibuat kecil agar bisa dimulai: “Kita mulai dari 10 menit, satu sudut, satu keputusan.” Bukan karena masalahnya kecil, tetapi karena langkah pertama harus cukup ringan untuk dilangkahi.
Untuk keluarga, yang paling sering perlu dilatih bukan tenaga, melainkan bahasa. Hindari label seperti “malas”, “jorok”, “keras kepala”, sebab label membuat orang bertahan, bukan berubah. Hindari pula pembersihan diam-diam—meski niatnya baik—karena rasa dikhianati bisa memperparah kecemasan dan memicu akuisisi ulang. Pilih bahasa keselamatan: “Aku khawatir jalur keluar tertutup kalau terjadi kebakaran,” jauh lebih membantu daripada “rumahmu memalukan.” Lalu tawarkan bantuan yang konkret dan terukur: menemani memilah 30 menit, membantu membuat sistem penyimpanan sederhana, atau menemani konsultasi. Bantuan yang realistis lebih berguna daripada ultimatum yang mustahil.
Untuk masyarakat, penting menggeser lensa: hoarding bukan tontonan, bukan komedi, bukan bahan olok-olok. Ini gangguan kesehatan jiwa yang berkelindan dengan keselamatan hunian dan kesehatan publik—risiko jatuh, kebakaran, sanitasi, beban caregiver, dan konflik sosial. Empati bukan berarti membiarkan. Empati berarti menolong dengan cara yang tidak melukai, tanpa merampas martabat orang yang sedang berjuang.
Di banyak rumah, perubahan besar hampir selalu dimulai dari sesuatu yang kecil: satu laci yang kembali bisa ditutup, satu jalur yang kembali bisa dilalui, satu keputusan yang tidak sempurna tetapi cukup—lalu diulang lagi besok. Bukan sebagai proyek heroik, melainkan sebagai latihan harian untuk merebut kembali ruang hidup.
(Dokter Dito Anurogo MSc PhD, WWPO Peace Ambassador untuk Indonesia, alumnus PhD dari IPCTRM College of Medicine Taipei Medical University Taipei Taiwan, dokter riset, pendidik/dosen di FKIK Unismuh Makassar, peneliti/Ilmuwan di Yayasan IMI, mendapatkan sertifikasi Project Management dari International Business Management Institute Berlin Germany, master trainer, penulis profesional berlisensi BNSP, reviewer puluhan jurnal Internasional-nasional, memiliki lebih dari 55 sertifikasi dan kompetensi multi-lintasdisiplin keilmuan, berpengalaman aktif di berbagai organisasi tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional, telah menerbitkan puluhan buku dan ratusan opini/artikel)