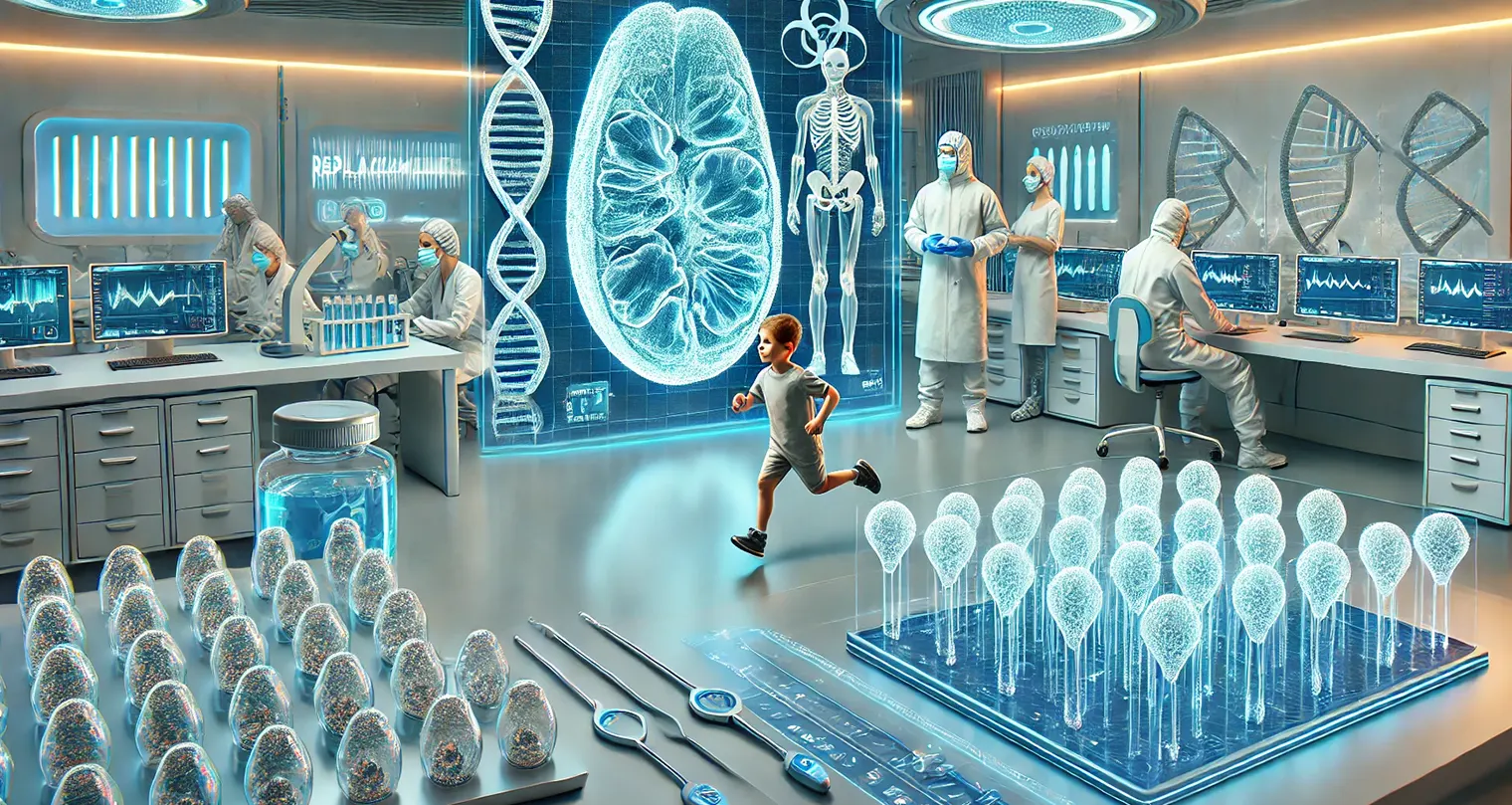Di IGD yang ramai, ada adegan-adegan kecil yang nyaris tak pernah masuk laporan resmi: troli tindakan berhenti karena jarum infus habis di laci yang keliru, petugas laboratorium menelpon ulang karena label sampel tidak terbaca, dokter jaga menunggu hasil pemeriksaan yang “katanya sudah dikirim” tetapi tersangkut di simpul administrasi, keluarga pasien mondar-mandir menanyakan hal yang sama karena informasi berpindah tangan tanpa jejak yang rapi. Semuanya terlihat sepele bila dipotong menjadi potongan-potongan, tetapi di rumah sakit, yang sepele sering menumpuk menjadi keterlambatan, kelelahan, biaya, dan—yang paling mengganggu nurani—risiko keselamatan pasien.
Di titik inilah Kaizen terasa relevan bukan sebagai jargon, melainkan sebagai cara kerja yang sederhana sekaligus keras kepala: memperbaiki hal-hal kecil yang membuat layanan menjadi lambat, rapuh, dan mudah salah. Kaizen bukan mengganti dokter dengan mesin, bukan pula menekan tenaga kesehatan agar “lebih cepat”. Kaizen justru merapikan sistem agar manusia bisa bekerja dengan waras: alat mudah ditemukan, alur jelas, informasi tidak tercecer, dan kesalahan diperlakukan sebagai sinyal untuk memperbaiki desain proses—bukan alasan untuk mencari kambing hitam.
Secara etimologis, Kaizen (改善) berasal dari dua kanji Jepang: kai—perubahan, dan zen—kebaikan. Terjemahan ringkasnya: perubahan menuju lebih baik. Tetapi di lapangan, Kaizen punya definisi yang lebih bernapas: perbaikan berkelanjutan yang dilakukan terus-menerus, melalui langkah kecil, oleh orang-orang yang menjalani pekerjaan itu setiap hari. Di rumah sakit, “orang-orang itu” bukan hanya manajer mutu atau tim akreditasi; mereka adalah perawat yang setiap shift melihat friksi kecil di bedside, analis lab yang tahu persis mengapa sampel sering tertahan, farmasis yang paham jam-jam puncak resep menumpuk, petugas rekam medis yang berhadapan dengan formulir ganda, sampai petugas kebersihan yang tahu ruangan mana paling sering “kecolongan” karena ritme kerja tidak realistis.
Kaizen berdiri di atas dua pilar yang—bila dipisahkan—membuatnya kehilangan jiwa. Pilar pertama adalah continuous improvement: keyakinan bahwa proses selalu bisa dibuat lebih aman, lebih ringkas, lebih jelas. Pilar kedua adalah respect for people: penghormatan pada manusia yang bekerja, termasuk hak mereka untuk didengar, untuk aman secara psikologis, dan untuk tidak disalahkan atas kegagalan sistem. Tanpa penghormatan pada manusia, Kaizen berubah menjadi proyek efisiensi yang membakar tenaga. Tanpa perbaikan berkelanjutan, penghormatan pada manusia tinggal slogan di spanduk.
Sejarah Kaizen sendiri lahir dari situasi yang tidak romantis: Jepang pasca-Perang Dunia II, ketika keterbatasan sumber daya memaksa ketelitian menjadi strategi bertahan hidup. Gerakan kualitas, quality circles, dan ide-ide tentang variasi proses serta manajemen mutu yang dipopulerkan tokoh seperti W. Edwards Deming dan Joseph Juran ikut membentuk lanskapnya. Toyota Production System kemudian membuat Kaizen identik dengan disiplin proses: aliran kerja yang baik mengurangi cacat, menurunkan biaya tersembunyi, dan menjaga martabat pekerja karena pekerjaan dibuat masuk akal.
Ketika gagasan ini menyeberang ke rumah sakit pada akhir 1990-an dan awal 2000-an, resistensinya wajar: “Rumah sakit bukan pabrik.” Keberatan itu valid, terutama bila orang datang membawa Lean seperti membawa penggaris untuk mengukur nyawa. Namun Kaizen di layanan kesehatan justru menemukan argumen paling kuatnya di tempat yang paling sensitif: kesalahan kecil bisa berakibat besar. Variasi pasien memang tidak bisa diseragamkan—dan tidak boleh diseragamkan—tetapi variasi proses yang tidak perlu sering menjadi sumber keterlambatan, kekeliruan, dan kepedihan yang seharusnya bisa dicegah. Jika sebuah sistem bisa dirancang agar mobil tidak cacat, mengapa sistem perawatan tidak dirancang agar obat tidak tertukar dan infeksi tidak mudah menyusup?
Di berbagai negara, rumah sakit yang mengadopsi Kaizen secara serius menunjukkan perubahan yang terasa: bukan hanya angka di dashboard, tetapi suasana kerja yang lebih tertib, percakapan lintas profesi yang lebih jujur, dan ruang bagi staf untuk berkata, “Ada yang tidak beres di proses ini,” tanpa takut dipermalukan. Dari situ, Kaizen pelan-pelan menjadi jembatan yang unik: menghubungkan klinik, manajemen, etika, dan realitas sosial—termasuk tuntutan akreditasi, kekurangan SDM, pandemi, dan transformasi digital yang kerap datang lebih cepat daripada kesiapan proses.
Kalau Kaizen diminta menjelaskan dirinya dalam bahasa rumah sakit, ia akan memulai dari perubahan cara bertanya. Dalam insiden keselamatan, pertanyaan paling lazim adalah “siapa yang salah?” Kaizen menggeser fokus menjadi “bagian mana dari sistem yang memungkinkan ini terjadi?” Perawat yang salah mengambil obat, misalnya, sering berdiri di ujung masalah: kemasan obat mirip, obat diletakkan berdampingan, ruangan bising, interupsi terjadi saat persiapan, dan prosedur verifikasi tidak dibuat praktis untuk jam sibuk. Kaizen tidak meniadakan tanggung jawab individu, tetapi menolak berhenti pada moral panic. Ia memaksa organisasi jujur pada desainnya sendiri.
Kaizen juga menuntut kepemimpinan keluar dari kantor menuju tempat kerja yang sesungguhnya. Orang Jepang menyebutnya gemba: lokasi nyata tempat nilai diciptakan. Di rumah sakit, gemba bukan ruang rapat, melainkan bedside pasien, ruang triase, farmasi, laboratorium, ruang operasi, loket pendaftaran, ruang tunggu. Gemba walk yang sehat bukan inspeksi untuk mencari salah; ia ritual belajar. Seorang pemimpin yang baik datang dengan mata terbuka dan mulut yang tidak sibuk menguliahi. Ia mengamati alur, melihat hambatan, lalu bertanya dengan nada yang membuat staf berani menjawab: “Apa yang paling menyulitkan Anda hari ini?” atau “Jika satu hal bisa diperbaiki agar pasien lebih aman, apa itu?”
Sering kali, temuan gemba bukan sesuatu yang dramatis, justru sesuatu yang memalukan karena terlalu sederhana. Misalnya, rute pasien stroke dari IGD ke CT-scan terhenti bukan karena kurangnya ahli saraf, melainkan karena verifikasi administrasi membutuhkan stempel tertentu pada jam tertentu. Di sinilah Kaizen memperlihatkan kecerdasannya: ia membedakan kompleksitas klinis yang memang rumit dari kompleksitas proses yang sebenarnya tidak perlu. Energi klinis seharusnya dipakai untuk menilai pasien, bukan untuk mengejar stempel.
Setelah melihat realitas, Kaizen bergerak dengan ritme saintifik. Siklus PDCA—Plan, Do, Check, Act—sering dipajang di poster, tetapi yang membuatnya hidup adalah disiplin untuk tidak melompat ke solusi sebelum masalah dipahami. Plan yang baik tidak berbunyi “meningkatkan mutu layanan”, melainkan spesifik dan terukur: “mengurangi waktu tunggu obat rawat jalan dari 70 menit menjadi 45 menit dalam 6 minggu.” Lalu Do: uji coba kecil dulu, bukan revolusi besar yang mengagetkan semua orang. Ubah layout meja resep untuk satu shift, coba antrian sederhana selama tiga hari, uji template edukasi pasien di satu poli. Kaizen menyukai eksperimen cepat, karena rumah sakit tidak punya kemewahan waktu untuk menunggu rapat berbulan-bulan.
Check kemudian dilakukan dengan data yang relevan, bukan data yang hanya cantik untuk presentasi. Kadang data itu cukup berupa stopwatch, tally sheet, audit sepuluh sampel, atau run chart harian. Yang penting, data menjawab pertanyaan, bukan sekadar memenuhi kewajiban laporan. Dan Act menuntut keberanian untuk menutup siklus: bila berhasil, standarkan dan sebarkan; bila gagal, pelajari dan ulangi. Di budaya yang mudah memalukan orang, kegagalan sering disembunyikan. Kaizen meminta sebaliknya: kegagalan diperlakukan sebagai pelajaran, selama ia terjadi dalam eksperimen yang terkendali dan bertujuan melindungi pasien.
Di antara semua alat Kaizen, ada satu yang terasa paling “mengganggu” ego profesi; berburu pemborosan. Dalam Lean, pemborosan (muda) adalah segala sesuatu yang menghabiskan waktu dan tenaga tanpa menambah nilai klinis. Di rumah sakit, pemborosan bukan hanya boros uang; ia boros rasa aman. Menunggu (waiting) membuat nyeri lebih lama, memperpanjang kecemasan, dan dalam kasus tertentu memperburuk outcome. Transportasi yang tidak perlu membuat pasien berpindah-pindah, menambah risiko jatuh dan infeksi. Gerakan berlebih (motion) membuat perawat berjalan seperti maraton hanya karena tata letak buruk—kelelahan naik, fokus turun. Kelebihan proses (overprocessing) membuat dokter dan perawat menjadi juru ketik data yang sama di tiga tempat. Cacat (defects) seperti label tertukar atau resep salah tulis memaksa pemeriksaan diulang, menambah paparan risiko. Inventori yang kacau—stok berlebih atau justru kosong—sama-sama berbahaya. Ada pula pemborosan yang paling menyedihkan: underutilized talent, ketika tenaga ahli mengerjakan hal yang seharusnya bisa didelegasikan karena sistem tidak mendukung, lalu pulang dengan perasaan “seharian saya tidak jadi dokter.”
Kalimat “fix flow, fix outcomes” terdengar seperti slogan, tetapi di rumah sakit ia sering terbukti lewat hal konkret. Menata ulang alur pengambilan darah dan pengiriman sampel bisa menurunkan turnaround time lab; keputusan klinis lebih cepat; lama rawat berkurang; biaya turun tanpa mengorbankan keselamatan. Bukan karena staf bekerja lebih keras, melainkan karena sistem berhenti mengganggu staf dengan friksi yang tidak perlu.
Namun, berburu pemborosan tidak akan lengkap tanpa kemampuan menggali akar masalah. Di sinilah disiplin “5 Whys” dan diagram Fishbone menjadi semacam kacamata baru. Ketika obat terlambat diberikan, respons tercepat biasanya menyalahkan farmasi atau perawat. Kaizen memaksa pertanyaan diulang sampai ketemu penyebab yang bisa ditindak: resep menumpuk di jam tertentu; jam tertentu itu terjadi karena jadwal poli selesai bersamaan; jadwal itu dibuat berdasarkan kebiasaan, bukan kapasitas proses. Dari sini, solusi bergeser dari “marahi unit” menjadi perbaikan desain: menyeimbangkan jadwal, membuat batching yang rasional, memperbaiki triase resep, atau menata ulang jalur komunikasi.
Fishbone menambah kedalaman dengan mengelompokkan penyebab pada manusia, metode, mesin/alat, material, lingkungan, pengukuran—dan, dalam konteks layanan kesehatan kita, sering perlu ditambahkan lapisan sosiologis dan politis: regulasi, rantai pasok nasional, insentif pembiayaan, ketimpangan akses, budaya organisasi, hingga dinamika geopolitik obat dan alat kesehatan yang membuat harga dan ketersediaan tidak selalu masuk akal. Kaizen yang dewasa berani berkata, “Saya perbaiki yang bisa saya kendalikan hari ini, dan saya dokumentasikan yang perlu advokasi sistemik.” Ia tidak naif, tetapi juga tidak menyerah.
Di tengah kompleksitas itu, standar sering dicurigai sebagai musuh profesionalisme. Padahal, dalam praktik klinik, standar yang tepat justru melindungi energi profesional untuk hal-hal yang benar-benar membutuhkan penilaian klinis. Standard work bukan membekukan akal sehat; ia mendokumentasikan cara terbaik yang diketahui saat ini untuk prosedur yang seharusnya konsisten: pemberian obat high-alert, checklist pra-operasi, komunikasi handover seperti SBAR (standar komunikasi terstruktur yang mendukung prinsip Kaizen; yaitu perbaikan berkelanjutan melalui kejelasan proses dan penghormatan pada manusia yang bekerja), protokol sepsis, standar triase. Standar membuat pelatihan lebih adil, variasi berbahaya turun, dan ketika terjadi deviasi, tim bisa mendiskusikannya dengan bahasa yang sama.
Lalu ada 5S—Sort atau Seiri (整理) atau ringkas, Set in order atau Seiton (整頓) atau rapi, Shine atau Seiso (清掃) atau resik, Standardize atau Seiketsu (清潔) atau rawat, Sustain atau Shitsuke (躾) atau rajin— yang sering diremehkan sebagai kegiatan rapih-rapih atau sekadar beres-beres. Di ruang tindakan, 5S adalah teknologi keselamatan yang tidak memerlukan listrik: alat yang mudah ditemukan mengurangi keterlambatan, label jelas mengurangi salah ambil, manajemen visual menurunkan beban kognitif, lingkungan rapi menurunkan stres. Rumah sakit yang baik tidak menunggu manusia selalu sempurna; ia mendesain proses agar manusia lebih mudah benar. Itu bukan sekadar manajemen, itu etika: mencegah mudarat lewat desain.
Etika yang sama muncul ketika kita bicara KPI. Di rumah sakit, apa yang diukur akan membentuk perilaku—dan KPI yang salah bisa menciptakan politik internal: unit saling menyalahkan, data “dirapikan” supaya terlihat bagus, atau layanan dipoles tanpa substansi. Kaizen menuntut KPI yang sedikit tetapi bermakna, seimbang antara kualitas klinis, keselamatan, pengalaman pasien, efisiensi, dan kesejahteraan staf. Ia juga menuntut kombinasi indikator lagging dan leading: angka infeksi dan mortalitas memang penting, tetapi kepatuhan kebersihan tangan, waktu respons, ketersediaan alat, audit proses, dan kualitas handover sering menjadi indikator yang lebih bisa dikendalikan tim. KPI dalam Kaizen bukan palu untuk menghukum; ia kompas untuk belajar—indikator yang mengundang percakapan, bukan mematikan percakapan.
Semua ini akan terdengar seperti modul pelatihan bila tidak kembali ke denyut harian rumah sakit. Kaizen, pada akhirnya, hidup sebagai kebiasaan kecil: rapat singkat di awal shift yang benar-benar membahas hambatan nyata; papan visual yang tidak hanya dipajang menjelang survei akreditasi; “ide perbaikan” yang tidak berakhir sebagai formulir, melainkan menjadi perubahan yang bisa disentuh; pemimpin yang datang ke gemba dan pulang membawa satu keputusan sederhana yang langsung mengurangi friksi; staf yang berani melaporkan near-miss karena mereka percaya organisasi ingin belajar, bukan mencari tersangka.
Di IGD yang sama, troli tindakan akhirnya berhenti “tersesat” setelah laci diatur ulang dan diberi label yang masuk akal. Hasil lab yang dulu sering terlambat mulai stabil setelah alur sampel dipangkas dari beberapa simpul yang hanya menambah antrean. Keluarga pasien tidak perlu bertanya berulang-ulang karena informasi dicatat dengan cara yang konsisten dan bisa diakses tim. Tidak ada keajaiban teknologi di sini—yang ada adalah kesediaan untuk melihat kenyataan, menghormati manusia yang bekerja, lalu memperbaiki proses sedikit demi sedikit, hari demi hari, pada titik-titik yang selama ini dianggap “memang begini dari dulu.”
Di antara suara monitor, panggilan ambulans, langkah cepat perawat, dan napas pasien yang kadang masih terengah, Kaizen terdengar seperti keputusan yang sunyi: membuat sistem berhenti menyulitkan orang-orang yang sedang berusaha menyelamatkan orang lain.
(Dokter Dito Anurogo MSc PhD, WWPO Peace Ambassador untuk Indonesia, alumnus PhD dari IPCTRM College of Medicine Taipei Medical University Taipei Taiwan, dokter riset, pendidik/dosen di FKIK Unismuh Makassar, peneliti/Ilmuwan di Yayasan IMI, mendapatkan sertifikasi Project Management dari International Business Management Institute Berlin Germany, master trainer, penulis profesional berlisensi BNSP, reviewer puluhan jurnal Internasional-nasional, memiliki lebih dari 55 sertifikasi dan kompetensi multi-lintasdisiplin keilmuan, berpengalaman aktif di berbagai organisasi tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional, telah menerbitkan puluhan buku dan ratusan opini/artikel)